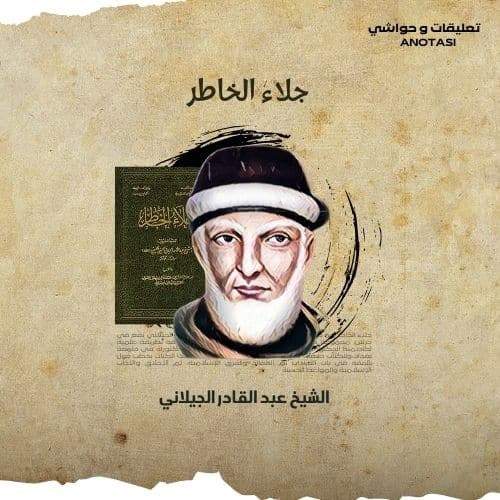“Tidak sedikit dari kalian melaksakan puasa karena mengikuti tradisi orang tua, teman, atau tetangga.”
Kutipan tersebut merupakan salah satu pernyataan Syaikh Abdul Qadir al-Jilani dalam Jalāul al-Khāṭir dalam bab haqīqat al-Ṣaum. Pernyataan itu muncul dari kritik Syaikh Abdul Qadir terhadap distorsi makna puasa sebagai amaliyah tradisi semata, bukan puasa sebagai ibadah. Dalam hal tersebut, puasa hanya dipahami sebatas pada dimensi eksoterik belaka yaitu dengan menahan diri dari lapar dan minum sehingga meninggalkan makna esoteris yang merupakan tujuan dari disyariatkannya ibadah puasa. Oleh karena itu, tulisan ini akan mengajak kita memahami hakikat puasa menurut kalangan sufi yang direpresentasikan oleh syaikh Abdul Qadir al-Jilani dalam Jalāul al-Khāṭir dan Syaikh Abdul Halim Mahmud dalam Shahru al-Ramaḍan.
Signifikansi puasa bagi kaum muslim adalah meraih atau meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Hal itu didasari atas firman Allah SWT:
يٰٓـاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا كُتِبَ عَلَيۡکُمُ الصِّيَامُ کَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيۡنَ مِنۡ قَبۡلِکُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُوۡنَۙ
“wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa” (Al-Baqarah: 183).
Menurut Abdul Halim Mahmud, nilai-nlai spiritual puasa—al-Rūḥāniyyat al-Ṣawm—terdapat pada akhir ayat tersebut yaitu pada kalimat: la’allakum tattaqūn (agar kamu bertakwa). Dalam mengartikan takwa, Syaikh Abdul Halim menjelaskan bahwa takwa terdiri dari dua unsur penting: Pertama, bersifat positif, yaitu melaksanakan segala perintah Allah dalam ucapan maupun perbuatan seperti mengajak kepada kebaikan dan melaksanakan perbuatan baik. Unsur kedua, mencegah setiap keburukan yang telah Allah larang dalam ucapan maupun tindakan seperti menggunjing dan menipu. (Abdul Halim Mahmud, 2000)
Dalam kalangan sufi, mereka memiliki interpretasi menarik dalam memaknai bulan Ramadan. Syaikh Abdul Qadir mengartikan Ramadan sebagai abreviasi dari sejumlah kata yang memiliki makna yang berhubungan dengan kalbu dan pahala. Bagi Syaikh Abdul Qadir, kata Ramadan terdiri lima huruf yaitu: Ra’, Mim, Ḍat, Alif, dan Nun.
Ra’ berasal dari raḥmah dan ra’fah yang berarti rahmat dan belas kasih; Mim berasal dari kata majāzah, maḥabbah, dan minnah yang berarti balasan, cinta dan anugerah; Ḍat berasal dari kata ḍiman li al-tsawāb yang berarti jaminan pahala; Alif berasal dari ulfah yang berarti pertemanan dan keharmonisan; terakhir Nun berasal dari nūr dan nawāl yang bermakna cahaya dan pemberian. Sehingga, menurut syaikh Abdul Qadir, jika seorang hamba dapat melaksanakan esensi bulan Ramadan, maka dia akan mendapat segala hal yang terdapat dari definisi Ramadan di atas. Di dunia, ia akan mendapatkan kekuatan dan cahaya hati, nikmat dan pemberian secara dhahir dan batin. Sementara di akhirat kelak, hamba tersebut mendapatkan sesuatu yang belum dipandang oleh mata, terdengar oleh telinga atau pun terbersit oleh hati manusia.
Untuk mencapai esensi puasa, kalangan sufi menekankan untuk berpuasa secara ikhlas kepada Allah dan menjauhi hal-hal haram baik dalam perbuatan, ucapan lisan dan hati. Pada esensinya, puasa adalah upaya menahan telinga, mata, tangan, kaki dan seluruh anggota tubuh lainnya serta hati dari perbuatan yang dapat menghilangkan esensi puasa.
Selain itu, penting dicatat, Syaikh Abdul Qadir juga menekankan dimensi sosial untuk menolong sesama manusia dengan memberikan makanan kepada fakir miskin. Dalam arti, jangan jadikan puasa sebagai cermin ketimpangan sosial seperti membiarkan orang lain kelaparan sementara orang-orang yang puasa kenyang dengan hidangan buka puasa. Walakhir, melalui ajaran-ajaran sufi terkait esensi puasa sebagaimana telah dipaparkan, semoga dapat menjadi refleksi dan titik balik ibadah puasa kita di penghujung bulan suci ini. Dan dijauhkan dari apa yang dideskripsikan oleh Nabi SAW:
“Betapa banyak orang berpuasa hanya merasakan haus dan lapar, dan betapa banyak yang mendirikan salat hanya mendapatkan lelah” (Sunan Ibnu Majah).
Wallahu A’lam