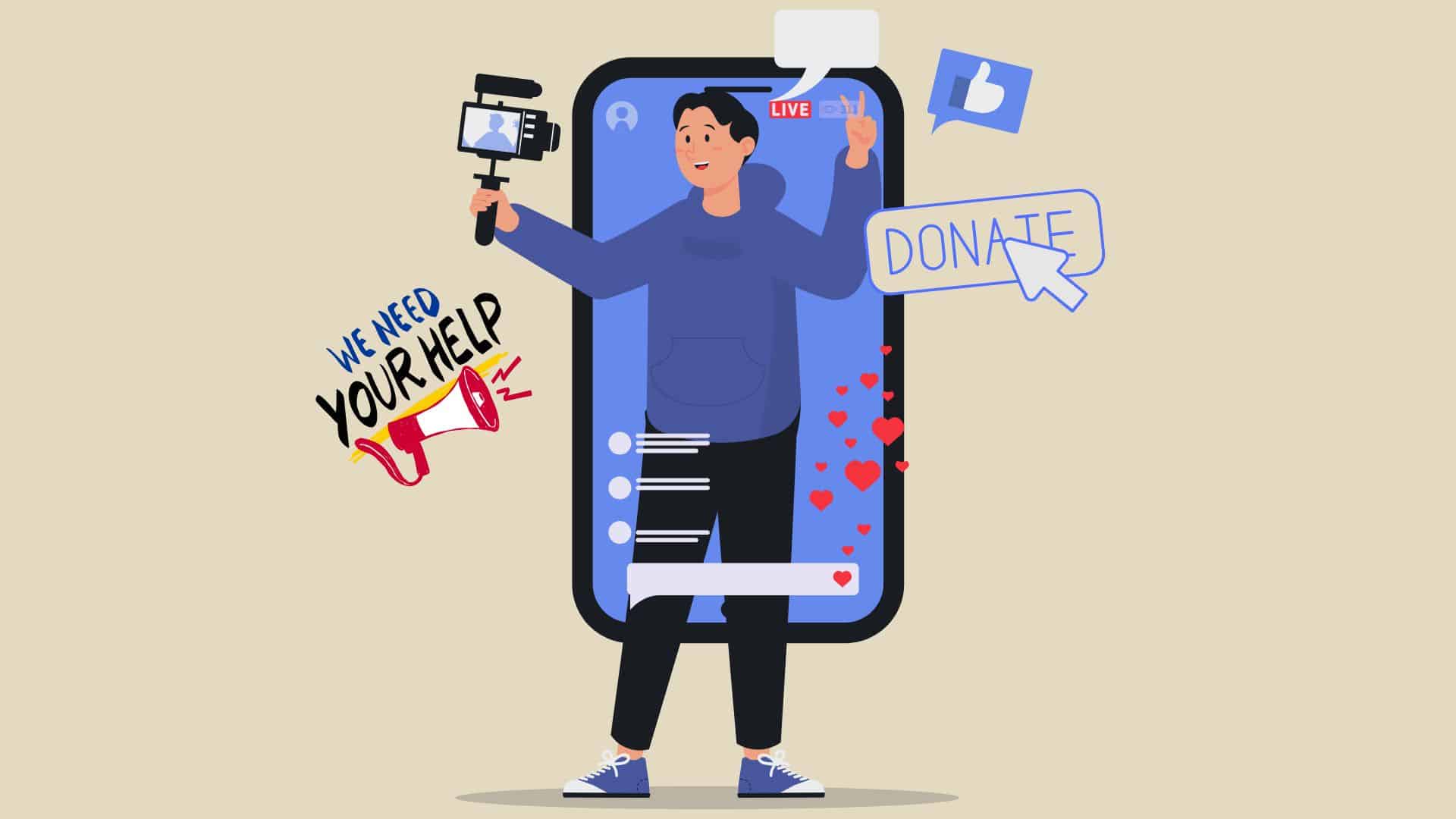Di era digital yang terintegrasi dengan arus informasi global, eksposur telah menjadi salah satu parameter utama dalam menentukan eksistensi individu maupun kelompok dalam percakapan publik. Media sosial, sebagai alat utama distribusi informasi, telah membuka ruang bagi siapa saja untuk berkontribusi pada narasi-narasi besar dan sering kali melalui isu-isu yang sedang viral. Namun, di balik fenomena ini, terdapat dilema moral yang perlu dikaji secara kritis: apakah eksposur yang dikejar dalam konteks ini benar-benar membawa manfaat substansial, atau justru menjadi manifestasi dari obsesi terhadap pengakuan sosial semata?
Dalam konteks kajian moral dan agama, niat menjadi fondasi utama yang menentukan nilai suatu tindakan. Rasulullah Ṣallá Allāhu ‘alayhi wa sallam bersabda:
إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ
“Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)
Pesan ini memberikan kerangka evaluatif yang relevan untuk menganalisis fenomena eksposur di era modern. Jika eksposur hanya dijadikan alat untuk memenuhi ego atau meningkatkan citra diri, maka tindakan tersebut berisiko kehilangan esensinya sebagai kontribusi yang tulus. Sebaliknya, ketika eksposur digunakan secara strategis untuk mendorong perubahan positif, hal itu memiliki potensi untuk menjadi alat transformatif.
Fenomena ini sering kali terlihat dalam bentuk tindakan seperti donasi yang dipublikasikan secara luas atau komentar terhadap isu-isu sensitif. Secara teori, tindakan semacam ini dapat memberikan dampak positif dengan menginspirasi orang lain untuk turut berkontribusi. Namun, praktiknya tidak selalu demikian. Donasi yang dipublikasikan secara berlebihan, tidak jarang dapat mereduksi martabat penerima manfaat dan menciptakan ketergantungan yang dikenal sebagai “dependency syndrome”. Dalam konteks ini, penerima bantuan sering kali kehilangan dorongan untuk mandiri karena terbiasa berada dalam posisi sebagai objek bantuan. Allah Subḥānahu wa Taʿālā berfiman dalam al-Qur’an:
إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ ۖ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ
“Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu.” (QS. Al-Baqarah: 271)
Dalam konteks ini, ayat di atas dapat ditafsirkan sebagai pentingnya menjaga keseimbangan antara transparansi yang bertujuan mendidik dan keikhlasan yang melindungi martabat individu.
Dari sudut pandang sosiologis, eksposur yang tidak terkontrol juga berisiko menciptakan informational noise, yakni kebisingan informasi yang mengaburkan inti masalah. Fenomena ini tampak jelas dalam isu-isu viral, di mana terlalu banyak konten yang dihasilkan tanpa substansi yang jelas. Akibatnya, perhatian publik terpecah, dan solusi nyata terhadap masalah yang sedang dibahas justru terpinggirkan. Selain itu, eksploitasi tragedi sebagai sarana untuk mendapatkan pengakuan sosial semakin memperparah kerentanan kelompok yang menjadi korban. Pendekatan ini tidak hanya tidak etis, tetapi juga kontraproduktif dalam membangun solidaritas sosial yang sehat.
Namun penting untuk diakui bahwa eksposur juga memiliki potensi positif jika dimanfaatkan secara bijak. Dalam konteks advokasi sosial, misalnya, eksposur dapat menjadi alat untuk meningkatkan kesadaran publik terhadap isu-isu yang kurang mendapat perhatian. Penggunaan media sosial untuk mendidik masyarakat tentang krisis lingkungan, kesehatan mental, atau ketidakadilan struktural merupakan contoh bagaimana eksposur dapat menjadi instrumen untuk perubahan sosial yang signifikan. Kuncinya terletak pada integritas pemberi pesan dan komitmen untuk menjaga narasi tetap fokus pada manfaat publik.
Untuk memastikan bahwa eksposur tidak kehilangan nilai moralnya, ada beberapa prinsip etis yang perlu dijadikan panduan. Pertama, setiap tindakan harus diawali dengan niat yang tulus untuk memberikan manfaat. Ini melibatkan refleksi mendalam tentang dampak jangka panjang, baik terhadap penerima manfaat maupun masyarakat luas. Kedua, transparansi harus diimbangi dengan sensitivitas. Publikasi yang menampilkan wajah atau kondisi penerima bantuan, misalnya, harus dilakukan dengan mempertimbangkan martabat individu tersebut. Ketiga, eksposur harus diarahkan pada edukasi, bukan eksploitasi. Dalam hal ini, penggunaan data yang akurat dan narasi yang empatik sangat diperlukan untuk menjaga kredibilitas.
Menunjukkan eksistensi di era viral bukanlah tindakan yang salah secara inheren. Namun, hal ini memerlukan keseimbangan yang hati-hati antara kepentingan pribadi dan tanggung jawab sosial. Dalam setiap tindakan, prinsip keikhlasan dan integritas harus tetap menjadi landasan, sebagaimana sabda Rasulullah Ṣallá Allāhu ‘alayhi wa sallam:
الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ وَلَا يُحَقِّرُهُ
“Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Dia tidak akan menzaliminya, tidak akan membiarkannya (tanpa bantuan), dan tidak akan merendahkannya.” (HR. Muslim)
Pentingnya menjaga martabat orang lain, terutama dalam konteks amal dan kontribusi sosial. Kegiatan yang dilakukan dengan niat yang benar dan pendekatan yang etis memiliki potensi untuk menjadi alat perubahan yang luar biasa. Namun, jika hanya digunakan untuk mengejar validasi sosial, maka ia tidak lebih dari cermin obsesi terhadap pengakuan semata. Wallahu A’lam bi al-Sawab