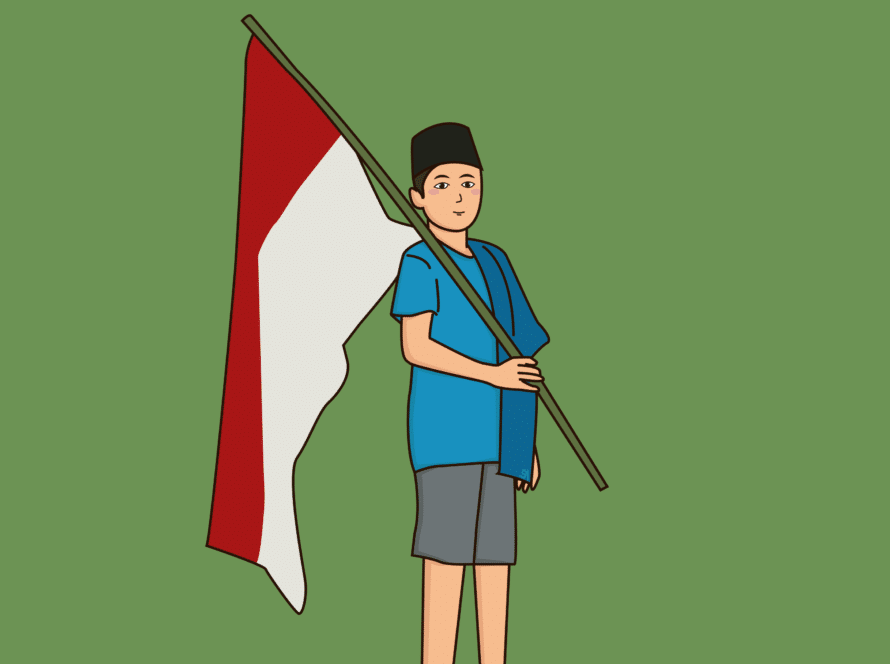Pasca-Pemilihan umum 2024, peta politik Indonesia mengalami dinamika yang mencolok dan bahkan mudah saja terprediksi. Partai-partai yang tidak berhasil memenangkan pemilu, kini sibuk berbondong-bondong dan berupaya masuk dalam struktur kekuasaan. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan besar: apakah pemilu di Indonesia hanya menjadi ajang pragmatisme politik, dan meniadakan ideologi yang semestinya dipertahankan?
Pragmatisme tampaknya menjadi kunci bertahan dalam arus cepat politik Indonesia. Partai yang kalah dalam pemilu sering kali melupakan platform ideologis yang mereka usung selama kampanye demi sebuah tempat dalam kabinet atau posisi strategis lainnya. Strategi ini, meskipun efektif untuk kelangsungan hidup politik jangka pendek, pada dasarnya mengikis integritas politik dan memudarkan esensi dari demokrasi yang seharusnya berlandaskan pada ideologi dan visi yang jelas.
Salah satu pendorong utama dari fenomena pragmatisme ini adalah biaya politik yang mahal. Untuk bertahan dalam persaingan politik, diperlukan dana yang tidak sedikit, sehingga partai sering kali terpaksa ‘menjual’ visi mereka demi mendapatkan dukungan finansial. Di sisi lain, proses kaderisasi yang seharusnya menjadi tulang punggung partai politik tampaknya hanya menjadi ajang pencitraan belaka tanpa ada substansi nyata dalam pembentukan karakter dan ideologi kader.
Dalam proses pragmatisme ini, masyarakat sering kali disuguhi narasi tentang persatuan dan gotong royong yang pada kenyataannya hanya bertujuan untuk mengamankan ‘kue kekuasaan’. Hal ini pada gilirannya mempengaruhi kualitas demokrasi Indonesia, di mana pemilu tidak lagi menjadi wadah penyaluran aspirasi masyarakat melainkan hanya menjadi ajang bagi elite politik untuk berbagi kekuasaan.
Dominasi pemilik modal baik secara finansial ataupun sosial, tidak hanya mempengaruhi keputusan partai tetapi juga cenderung mengontrol arah kebijakan publik yang diambil, dan bahkan tidak jarang lebih mengutamakan kepentingan mereka dibanding kepentingan masyarakat luas. Keberadaan mereka di puncak piramida kekuasaan memperkuat siklus, di mana ideologi dan prinsip, sering kali dikalahkan oleh tawaran dana dan dukungan sosial.
Akibat dari hilangnya ideologi sebagai pemandu arah, masyarakat menjadi kurang berdaya dalam menuntut akuntabilitas dari para pemimpin mereka. Narasi yang digunakan oleh elite politik sering kali berubah sesuai kepentingan jangka pendek, bukan berdasarkan nilai atau visi jangka panjang. Akibatnya, demokrasi berisiko menjadi tidak lebih dari sekadar prosedur tanpa substansi, di mana pemilihan umum tidak lagi memenuhi fungsi aslinya sebagai alat untuk memilih pemimpin yang benar-benar mewakili aspirasi dan kepentingan rakyat.
Terkikisnya ideologi demi pragmatisme membawa dampak yang signifikan terhadap struktur politik dan kualitas demokrasi Indonesia. Fenomena ini menunjukkan perlunya refleksi mendalam dari semua pihak yang terlibat dalam perpolitikan Indonesia untuk kembali kepada prinsip-prinsip ideologis partai yang harusnya menjadi dasar dalam membuat kebijakan dan mengambil keputusan. Perjuangan untuk memperkuat kaderisasi yang berbasis ideologi, mengurangi ketergantungan terhadap dana politik besar, dan memperkuat mekanisme demokrasi yang berprinsip adalah langkah penting yang perlu segera diambil demi memperbaiki dan memajukan demokrasi kita.
Tanpa langkah konkret tersebut, politik di Indonesia akan terus terperosok dalam lingkaran setan yang pada akhirnya hanya merugikan rakyat yang seharusnya diwakili aspirasinya.